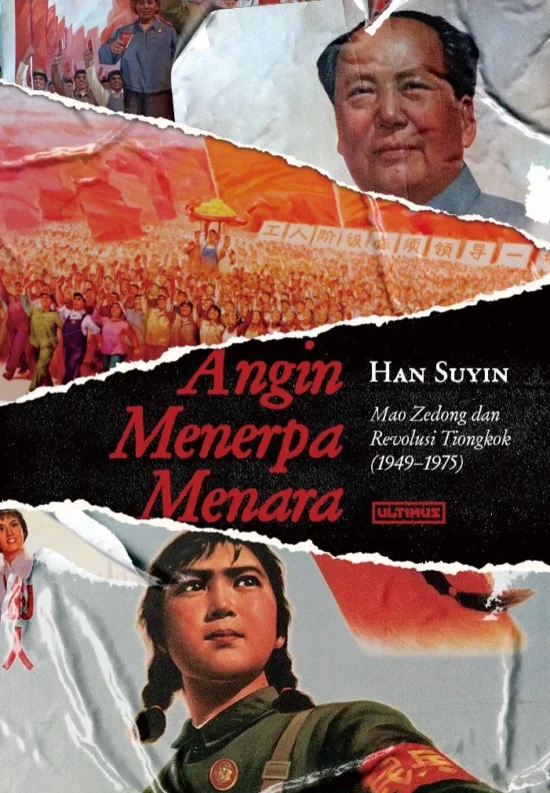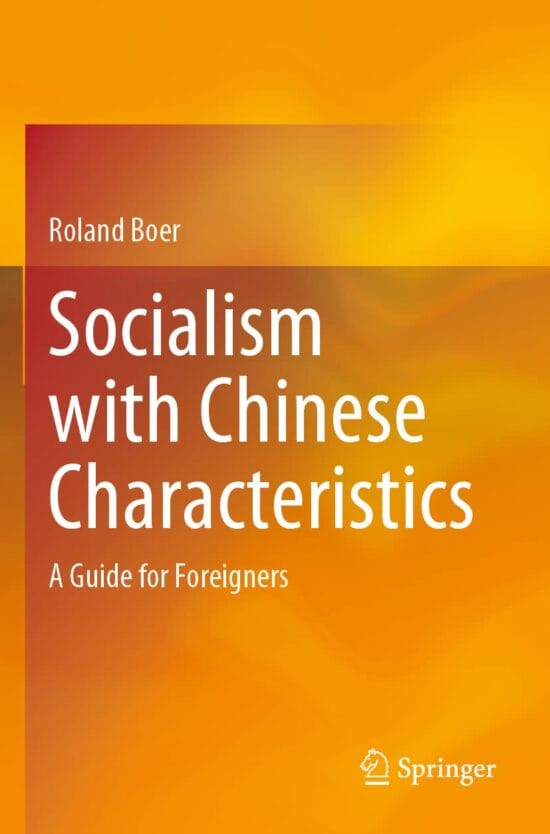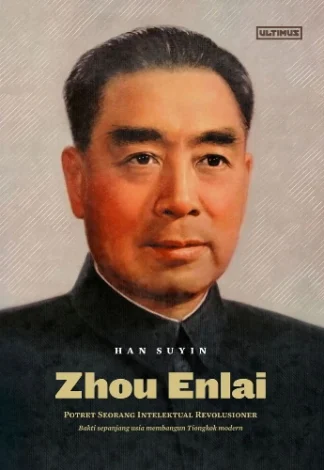Klaim-klaim Barat terbantahkan oleh bukti-bukti empiris.
Oleh

Politisi dan jurnalis Barat sering menyatakan bahwa Tiongkok sedang melakukan ‘kolonialisme’ di Afrika. Narasi ini berakar pada diskursus pemerintah AS yang telah ada selama hampir dua dekade, dan ini tercermin dalam sidang dengar pendapat Kongres AS yang digelar dengan tajuk utama “Tiongkok di Afrika: Kolonialisme Baru?”. Di tahun yang sama, majalah bisnis AS Forbes menyatakan bahwa tujuan keterlibatan Tiongkok di Afrika adalah “untuk mengeksploitasi rakyat dan mengambil sumber daya mereka. Sama dengan yang dilakukan oleh penjajah Eropa… hanya saja lebih buruk.”
Tentu ada alasan untuk mengkritik aktivitas perusahaan-perusahaan Tiongkok di Afrika, namun menyatakan bahwa Tiongkok menjalankan kekuasaan kolonial di benua tersebut—menyamakannya secara langsung dengan kolonialisme dan imperialisme Barat—adalah keliru secara empiris, mendistorsi istilah-istilah tersebut hingga menjadi tak bermakna, dan sama saja dengan menyangkal kekerasan dari kolonialisme yang sesungguhnya.
Apa itu kekuasaan kolonial?
Pertama, mari kita pertimbangkan konsekuensi dari tuduhan tersebut. Apa yang membentuk kekuasaan kolonial dan neokolonial?
Kolonialisme Eropa didasarkan pada invasi dan pendudukan militer, perampasan paksa, serta kekerasan sistematis, termasuk kelaparan yang dipicu oleh penerapan kebijakan secara paksa, kamp konsentrasi, dan genosida. Di Afrika saja, Inggris, Jerman, Prancis, Belgia, dan Italia semuanya pernah melakukan kejahatan genosida dalam berbagai peristiwa terpisah. Penjajah Jerman memusnahkan mayoritas populasi Herero dan Nama di Namibia. Penjajah Belgia membunuh sekitar 10 juta orang di Kongo.
Bangsa Afrika meraih kemerdekaan politik pada pertengahan abad ke-20, namun negara-negara inti terus menjalankan kekuasaan koersif di benua tersebut berdekade-dekade setelahnya. AS saat ini memiliki 58 pangkalan militer aktif di Afrika. AS telah mengintervensi banyak pemilihan umum nasional, mendistorsi proses demokrasi demi kepentingan AS, dan telah melakukan sekitar 20 operasi perubahan rezim. AS juga telah menjatuhkan sanksi ekonomi pada sebagian besar negara Afrika (semuanya kecuali 9 negara).
Prancis, di sisi lain, mengendalikan mata uang 14 negara Afrika Barat, dan menempatkan puluhan ribu tentara di bekas koloninya Afrika. Prancis memiliki rekor panjang dalam mencurangi pemilu di Afrika dan menyokong diktator, serta terlibat dalam pembunuhan beberapa pemimpin politik di Afrika sejak dekolonisasi formal. Adapun Inggris, mereka telah menginvasi hampir setiap negara Afrika (kecuali 5 negara), dan saat ini mempertahankan 18 pangkalan militer di benua tersebut.
Negara-negara Barat telah mendalangi kudeta terhadap puluhan pemerintahan progresif di seluruh belahan Bumi Selatan. Di Afrika, ini termasuk terhadap Patrice Lumumba di Republik Demokratik Kongo (RDK), Kwame Nkrumah di Ghana, dan Thomas Sankara di Burkina Faso, di antara banyak lainnya, yang semuanya digantikan oleh kediktatoran sayap kanan atau junta yang lebih bersedia melayani kepentingan Barat. Negara-negara Barat juga aktif mendukung rezim apartheid di Afrika Selatan.
Kekuasaan neokolonial juga dijalankan melalui lembaga keuangan internasional. Di IMF dan Bank Dunia, AS memegang hak veto atas semua keputusan besar dan negara-negara inti mengendalikan mayoritas suara. Mereka menggunakan kekuatan ini untuk memaksakan program penyesuaian struktural (Structural Adjustment Programmes atau SAPs) di seluruh wilayah belahan Bumi Selatan, secara paksa mengatur ulang produksi Selatan agar beralih dari produksi untuk kebutuhan orang-orang di tingkat lokal menuju produksi untuk kepentingan ekspor ke negara-negara inti dalam posisi subordinasi dalam rantai komoditas global. Di Afrika, SAPs menyebabkan resesi ekonomi dan kemunduran pembangunan selama berdekade-dekade demi memastikan sumber daya Afrika tetap tersedia secara murah bagi Barat.
Apa yang dilakukan Tiongkok di Afrika tidak ada apa-apanya dibanding semua hal tersebut. Perbedaan moral dan materialnya sangat besar. Tiongkok tidak melakukan pendudukan militer di Afrika. Tiongkok tidak melakukan operasi perubahan rezim, pembunuhan, dan kudeta. Ia tidak mengendalikan mata uang Afrika. Tiongkok tidak menjatuhkan sanksi atau program penyesuaian struktural pada ekonomi Afrika. Tiongkok juga tidak pernah menginvasi negara Afrika mana pun.
Tentu saja, Tiongkok belum pernah menginvasi negara mana pun dalam 46 tahun terakhir. Selama periode yang sama, kita telah menyaksikan negara-negara Barat melakukan invasi dan pengeboman terhadap banyak negara di belahan Bumi Selatan dengan tingkat kekerasan yang luar biasa, termasuk terhadap tujuh negara pada tahun 2025 saja.
Menyamakan aktivitas Tiongkok di Afrika dengan kolonialisme Eropa dam imperialisme Barat kontemporer tidak hanya keliru secara empiris, tetapi juga meremehkan kekerasan luar biasa yang dilakukan negara Barat. Ini secara efektif merupakan bentuk penyangkalan kolonial (colonial denialism).
Menilai tuduhan-tuduhan tersebut
Klaim mengenai ‘kolonialisme’ Tiongkok di Afrika berpusat pada tiga tuduhan utama. Pertama adalah perusahaan Tiongkok melakukan pelanggaran tenaga kerja dan menyebabkan konflik sosial serta lingkungan di Afrika. Kedua adalah Tiongkok mendominasi industri ekstraktif di Afrika. Ketiga adalah Tiongkok menjebak negara-negara Afrika dalam ‘perangkap utang’.
Terhadap klaim pertama: benar bahwa Tiongkok memiliki perusahaan kapitalis yang beroperasi di Afrika yang mengeksploitasi pekerja. Dan memang begitulah cara semua perusahaan kapitalis beroperasi, di mana pun kantor pusat mereka berada. Sebuah studi terbaru tentang Angola dan Ethiopia tidak menemukan perbedaan sistematis terkait upah yang dibayarkan oleh perusahaan Tiongkok dibanding dengan perusahaan Barat. Jika perilaku eksploitatif oleh perusahaan kapitalis menjadi definisi ‘kolonialisme’, maka istilah tersebut akan kehilangan semua nilai analitisnya. Kita bisa saja mengatakan bahwa perusahaan Indonesia atau Brasil yang beroperasi di Afrika adalah kolonial, namun jika demikian, istilah tersebut jelas jadi kehilangan maknanya.
Mengenai perusahaan Tiongkok yang menyebabkan konflik, sebuah studi terbaru tentang perusahaan pertambangan Tiongkok yang beroperasi di luar negeri [tanpa berusaha mentolerir yang dilakukan Tiongkok—editor] menemukan bahwa mereka tidak menciptakan lebih banyak konflik dibanding perusahaan milik asing lainnya. Faktanya, sebuah studi terhadap lebih dari 3.300 konflik keadilan lingkungan di seluruh dunia menemukan bahwa, ketika perusahaan asing memicu konflik di Afrika dan wilayah Bumi Selatan lainnya, perusahaan-perusahaan ini sebagian besar berkantor pusat di Barat ketimbang di Tiongkok. Dalam basis data yang sama (Environmental Justice Atlas), perusahaan Prancis bertanggung jawab atas konflik lingkungan di Afrika 50 kali lebih banyak daripada perusahaan Tiongkok berdasarkan perhitungan per kapita.
Terhadap klaim kedua, mengenai ekstraksi sumber daya: narasi bahwa Tiongkok mendominasi industri ekstraktif Afrika tidak terbukti. Pada tahun 2022, 72% dari dana eksplorasi pertambangan yang difokuskan pada Afrika dimiliki oleh perusahaan Kanada, Australia, dan Inggris, dengan hanya 3% dari Tiongkok. Dari data tahun 2018 menunjukkan bahwa perusahaan Tiongkok mengendalikan kurang dari 7% dari total nilai produksi tambang Afrika —kurang dari setengah nilai yang dikendalikan oleh satu perusahaan multinasional Inggris, Anglo American.
Jika melihat lebih dekat pada bahan bakar fosil, rencana perusahaan-perusahaan Barat untuk memperluas ekstraksi minyak dan gas di Afrika melampaui rencana perusahaan Tiongkok dengan perbandingan sembilan kali lipat. Dari 23 investor institusi terbesar dalam ekspansi bahan bakar fosil di Afrika, 92% investasinya dipegang oleh Barat; sementara itu 74% pembiayaan ekspansi disediakan oleh bank-bank Barat. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Barat-lah yang secara dominan mengendalikan dan meraup keuntungan dari ekstraksi bahan bakar fosil di Afrika.
Republik Demokratik Kongo (RDK) menyajikan kasus yang menarik. Pada tahun 2008, perusahaan Tiongkok menandatangani kesepakatan dengan RDK untuk melakukan pembangunan infrastruktur sebagai imbalan atas mineral bernilai hingga $50 miliar selama 25 tahun. Lembaga-lembaga Barat merepresentasikan hal ini sebagai ‘Kolonialisme Tiongkok’. Belakangan, pada tahun 2025, AS menandatangani kesepakatan dengan RDK untuk memperoleh hak mineral senilai $2 triliun sebagai imbalan atas penghentian serangan oleh milisi yang didukung Rwanda terhadap RDK; serangan yang diduga selama ini didukung oleh AS sendiri. Kesepakatan AS tersebut 40 kali lebih besar dibanding kesepakatan Tiongkok. Namun lembaga-lembaga Barat tidak menuduh AS melakukan kolonialisme; sebaliknya, mereka cenderung menggunakan narasi ‘perjanjian damai’.
Terakhir, mengenai pertanyaan tentang ‘perangkap utang’. Data yang ada menunjukkan bahwa hanya 12% dari utang luar negeri Afrika yang dipinjam dari Tiongkok, sedangkan 35% —tiga kali lipat lebih banyak—dipinjamkan dari kreditur swasta Barat, dan utang Afrika kepada kreditur Barat membawa bunga dua kali lipat dibanding dengan utang kepada Tiongkok.
Sebuah studi komprehensif tentang pinjaman Tiongkok ke Afrika selama periode 2000-2019 menemukan bahwa Tiongkok tidak pernah menyita aset dan tidak pernah menggunakan pengadilan untuk memaksakan pembayaran. Selain itu, selama pandemi Covid, Tiongkok menangguhkan volume utang yang jauh lebih besar untuk negara-negara berpenghasilan rendah dibanding yang dilakukan oleh kreditur Barat.
Mungkin yang paling penting, Tiongkok tidak menyertakan syarat-syarat penyesuaian struktural pada pendanaannya. Sebaliknya, kreditur Barat memiliki rekam jejak dalam memanfaatkan program penyesuaian struktural untuk memaksa pemerintah negara-negara Afrika menjual aset publik mereka.
Tiongkok dalam perspektif sistem-dunia
Penting untuk tetap menjaga perspektif di sini. Kekuatan imperialis berarti AS dan sekutunya bisa dan benar-benar bisa rutin menghancurkan seluruh negara di belahan dunia lain, melanggar hukum internasional lewat impunitas. Mereka dapat dan benar-benar melakukan pengeboman terhadap individu atau gerakan apapun yang tidak mereka sukai, di mana pun di planet ini, untuk alasan apa pun. Mereka dapat dan telah menjatuhkan sanksi yang melumpuhkan, membunuh jutaan orang dan memaksa pemerintah (negara lain) untuk tunduk pada kehendak mereka.
Tiongkok sama sekali tidak memproyeksikan kekuatan semacam ini. Ia adalah ekonomi semi-periferi, dengan PDB per kapita yang 80% lebih kecil dari negara inti, setara dengan rata-rata Amerika Latin. Pengeluaran militer per kapita-nya 40% lebih kecil dari rata-rata dunia, dan seperdua puluh (1/20) dari pengeluaran Amerika Serikat. Tiongkok dapat menolak dikte dari negara-negara inti sampai batas tertentu, tetapi ia tidak dapat dan benar-benar tidak memaksakan kehendaknya pada seluruh dunia seperti yang dilakukan negara-negara inti.
Semua ini bukan berarti perusahaan Tiongkok tidak mengeksploitasi pekerja dan sumber daya di Afrika. Namun hal ini tidak dapat digambarkan sebagai kekuasaan kolonial atau imperial tanpa membuat istilah-istilah ini menjadi tidak bermakna secara analitis, dan menyangkal kekerasan dari kolonialisme yang sebenarnya.
Negara-negara semi-periferi seperti Tiongkok memainkan peran perantara dalam sistem-dunia kapitalis. Mereka menyediakan barang-barang manufaktur murah ke negara-negara inti dalam industri yang sangat kompetitif dengan margin keuntungan yang sangat tipis. Para kapitalis yang beroperasi di industri ini berada di bawah tekanan untuk memperoleh input material semurah mungkin, yang mendorong mereka untuk mengeksploitasi sumber daya di wilayah periferi (seperti Afrika), di mana intervensi imperialis oleh negara-negara inti telah melemahkan pemerintah serta memurahkan tenaga kerja dan sumber daya.
Dalam sistem ini, negara inti mengekstrak nilai dari negara semi-periferi —termasuk dari Tiongkok— maupun dari periferi melalui semi-periferi. Perilaku kapitalis semi-periferi di wilayah periferi harus dipahami terutama sebagai fungsi dari sistem-dunia imperialis, alih-alih sebagai ekspresi dari imperialisme itu sendiri.
Tentang penulis
Jason Edward Hickel adalah seorang antropolog ekonomi asal Swazi, akademisi, dan seorang eko-sosialis demokratis. Saat ini, ia menjabat sebagai profesor di Institute of Environmental Science and Technology (ICTA-UAB) di Autonomous University of Barcelona. Ia merupakan anggota kehormatan (Fellow) dari Royal Society of Arts, peneliti tamu senior di International Inequalities Institute di London School of Economics, dan pernah menduduki posisi Chair of Global Justice and the Environment di University of Oslo. Ia juga bertugas di Climate and Macroeconomics Roundtable dari US National Academy of Sciences.
Penerjemah
Miftahu Ainin Jariyah, ilustrator dan desainer grafis lepas.