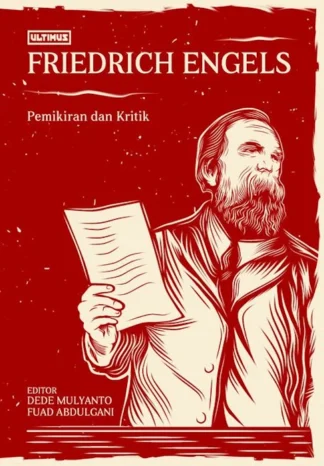oleh , Pengajar Sosiologi SMA
Tulisan ini sebelumnya berjudul “Friedrich Engels Pemikiran dan Kritik 3 Bab Pertama: Perjalanan Intelektual, Ekologi Manusia, dan Perang Petani Suci”. Ditujukan untuk forum belajar mingguan Rosa Sosial Studies. Membedah tokoh Friedrich Engels lewat buku Friedrich Engels: Pemikiran dan Kritik.
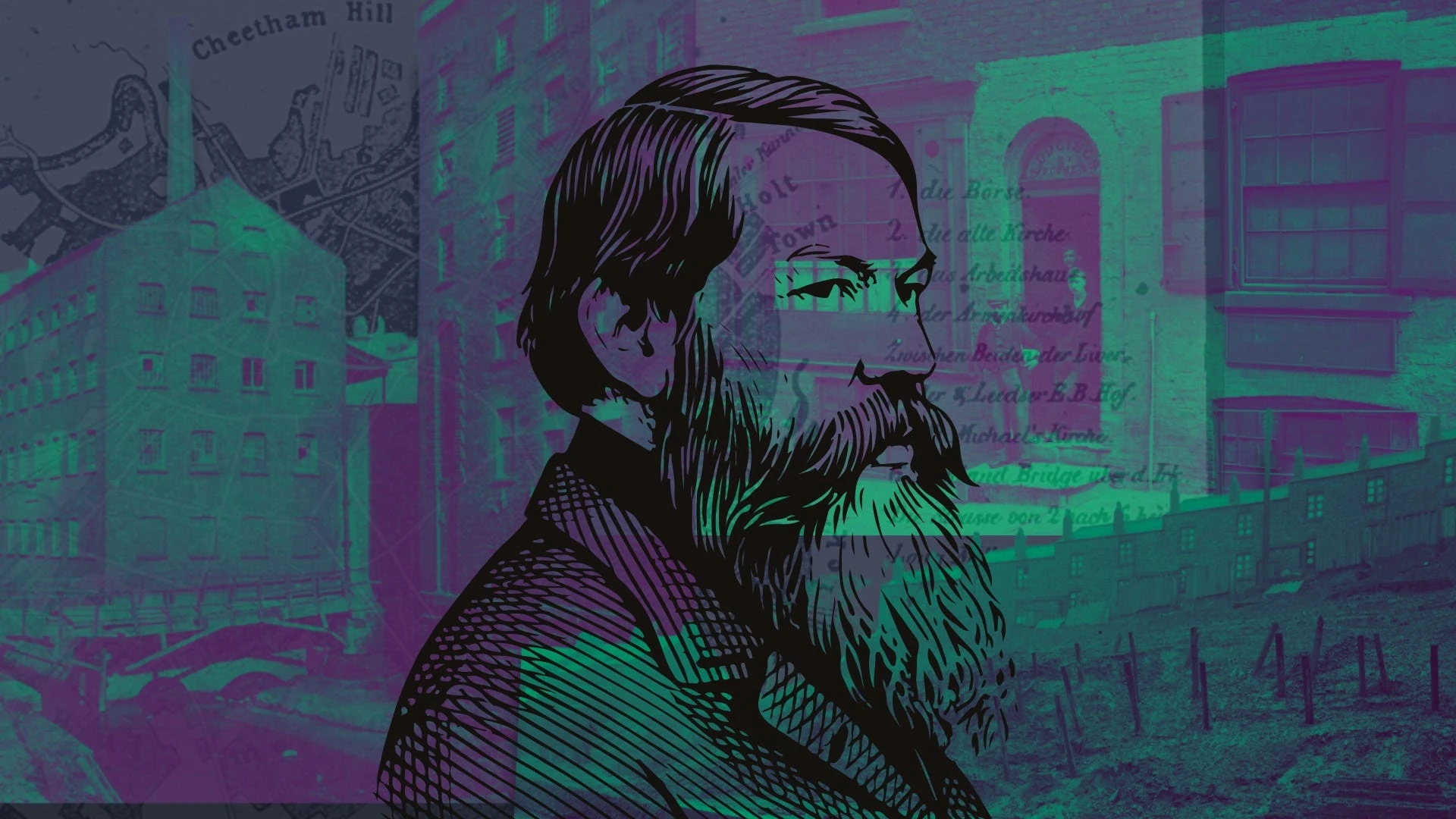
Buku ini adalah buku peringatan kelahiran yang ke-200, yang jatuh pada 28 November 2020 dengan menampilkan napak tilas dan pemikiran seorang sosok intelektual signifikan bernama Friedrich Engels. Engels jarang diketahui publik termasuk pemelajar-pemelajar ilmu sosial arus utama; bagaimana perannya sebagai kolaborator Karl Marx, sekaligus turut membangun jenama produksi pengetahuan serta agenda politik kelas pekerja itu sebagai ideologi Marxisme atau Marxian–alih-alih ‘Engelsian’, yang kelak menjadi ideologi resmi satu pertiga dunia. Saya akan merangkum tiga bab pertama dari Friedrich Engels Pemikiran dan Kritik (2020) ini lalu memberikan refleksi singkat atas itu.
Bagian pertama adalah tentang perjalanan seorang yang dijuluki Komunis Perlente, kata Rio Apinino, penulisnya. Engels dengan cerdik mampu memanfaatkan privilesenya sebagai orang kaya untuk mengembangkan hal yang dapat dimanfaatkan penduduk mayoritas planet bumi, kaum pekerja atau buruh, berupa ilmu pengetahuan beserta agenda politiknya. Pengalamannya sebagai juru tulis di perusahaan memberikan kesadarannya tentang masalah yang sedang dialami oleh mayoritas.
Revolusi industri telah melahirkan neraka dunia; bertolak belakang dari kondisi orang-orang kaya yang berumah megah dan wangi, Rio Apinio selanjutnya menuliskan:
…anak-anak ingusan dipekerjakan paksa dengan upah hanya tiga butir kentang, bedeng berisi buruh yang tidur berjejer seperti ikan teri, orang-orang cacat seumur hidup karena kecelakaan kerja bergelimpangan di pinggir jalan.
Engels melakukan aktivitas semacam Turba1 dengan didampingi oleh seorang buruh perempuan asal Irlandia yang sekaligus menjadi kekasih hatinya seumur hidup, Mary Burns. Turba yang dilakukan Engels tersebut menghasilkan catatan etnografi berjudul Kondisi Kelas Pekerja di Inggris yang diterbitkan pada 1845. Dari sana ia percaya buruh sendiri yang bakal memperbaiki kondisi mereka dengan pemberontakan.
Kepercayaan itu dipegang teguh oleh Engels dan semakin berkembang melalui perjalanan intelektualnya. Ibunya turut menyuburkan keyakinan anak laki-laki sulungnya itu dengan diam-diam mengirim karya tulis intelektual Jerman dan Prancis—karena diawasi ketat oleh bapaknya . Di kemudian hari ia dikirim bapaknya untuk wajib militer di Berlin; tempat yang juga bergejolak dengan budaya baru berupa munculnya forum-forum dan kelompok diskusi filsafat. Sekali berdayung dua tiga pulau terlampaui, merupakan adagium yang tepat dalam menggambarkan kecenderungan belajar seorang Engels. Di samping merasakan suasana kemiliteran—yang nantinya juga ia pelajari dengan amat baik, ia juga tidak luput untuk memanfaatkan gejolak budaya yang sedang digandrungi penduduk sipil di Berlin. Di sana ia juga sempat bertemu dengan kelompok Hegelian Muda yang kelak ia kritik sendiri melalui pamfletnya yang berjudul Sosialisme: Utopis dan Ilmiah pada 1880. Baginya sosialisme muncul dari masyarakat itu sendiri sebagai konsekuensi tidak terdamaikannya antagonisme kelas, alih-alih diisolasikan secara eksperimental pada suatu masyarakat apalagi sebatas kajian akademik tekstual yang banyak dilakukan kelompok Hegelian Muda.
Lenin memuji Engels sebagai guru proletariat modern terbaik; perjalanan sebagai intelektual independen dan materialis juga tertuang pada karyanya berjudul Asal-usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi, dan Negara. Dalam karyanya yang ditulis di masa tuanya itu (1884), Engels dengan pendekatan antropologi-sejarahnya berusaha membongkar hingga ke akar-akarnya; bagaimana penindasan manusia atas manusia lain, serta lahirnya watak patriarki yang menyertainya muncul di masyarakat.
Kapasitas Engels yang terjelaskan di atas itu menunjukkan bahwa ia tak mungkin hanya membeo terhadap Karl Marx. Engels sejak lama keluar dari koridor hidup aristokrat borjuasi. Menjadi radikal. Memberontak. Dan seringkali bertentangan dengan prinsip sang bapak sendiri, Friedrich Engels Sr. Tanpa meninggalkan sumber material sebagai seorang dari keluarga kaya raya, Engels turut menyokong kebutuhan hidup Marx dan keluarganya tidak kurang dari 40 tahun hidup.
Marx dan Engels sendiri mulai bertemu–dan saling berkorespondensi–melalui koran radikal jerman bernama Rheinische Zeitung. Dari sana, mereka menghasilkan ratusan artikel termasuk karya-karya monumental: Keluarga Suci, Ideologi Jerman, Manifesto Komunis, dan Das Kapital. Mereka berdua mengembangkan sistem pemikiran Marxisme yang berintikan bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas: masyarakat yang terdiri dari kelas-kelas antagonistik yang saling berseteru; bagaimana dalam tiap-tiap moda produksi sudah terkandung cikal bakal masyarakat baru yang diperoleh melalui revolusi; hingga dalam situasi apa komunisme mungkin dicapai.
Mahakarya keduanya masih dikembangkan hingga hari ini meski keduanya telah wafat; Marx pada 14 Maret 1883 dan Engels menyusul 12 tahun kemudian, 5 Agustus 1895.
Setelah menapak tilas perjalanan intelektual seorang komunis perlente, kita bertemu pada bagian kedua yang berjudul Pemikiran Ekologis Friedrich Engels: Tawaran Menuju Ekologi Manusia oleh Fuad Abdulgani. Di sana, Engels–dan Marxisme–dengan sosialisme sebagai solusi ilmiah atas segala kontradiksi yang ditimbulkan oleh adanya moda produksi kapitalisme sesungguhnya telah mengantisipasi isu populer paling krusial hari ini: krisis ekologi. Abdulgani dengan percaya diri menyebutkan bahwa Engels telah mengingatkan krisis ekologi sebagai bagian inheren kontradiksi kapitalisme sejak 150 tahun yang lalu, jauh sebelum Pertobatan Ekologis menjadi jargon umum yang mempedomani banyak penduduk bumi agar bersikap lebih bijaksana pada lingkungan, berorientasi pada kehidupan keberlanjutan. Karenanya isu ekologis sebetulnya imanen dalam pendekatan Marxis–sejak awal.
Di lain sisi, Engels dalam karya penulisannya juga disebut menjadi pionir gaya laporan lapangan etnografis–sekalipun tidak terafiliasi dengan para pionir antropologi. Tulisan pertamanya saat masih tergabung Hegelian Muda berjudul Letters from Wuppertal menggambarkan lingkungan sungai Wupper di daerah paling industrial di Eropa saat itu dengan rinci,
Gelombang berwarna ungu dari aliran sungai…warna merah menyala…bukan berasal dari pertempuran berdarah…melainkan dari sejumlah kerja pencelupan menggunakan pewarna…
Kita bisa melihat lagi kecenderungan penulisan Engels itu dalam karyanya Kondisi Kelas Pekerja di Inggris. Pengamatan yang dilakukannya adalah dengan cara melibatkan diri dengan subjek penelitian sehingga mendapatkan data primer tangan-pertama. Data itu kemudian dipadukan dengan telaah atas dokumen dan laporan kuantitatif maupun kualitatif sebelumnya, dan pada tahapan yang terakhir melakukan interpretasi melalui bingkai teoretik ekonomi-politik yang belum jamak dilakukan ilmuwan saat itu.
Dari karya tersebut pula (Kondisi Kelas Pekerja di Inggris)—beserta metodenya, Engels berhasil mengamati dengan rinci bagaimana berbagai faktor lingkungan berdampak pada kondisi fisik (kesehatan) populasi buruh. Yang mana mencerminkan konsep dasar dalam kajian ekologi, yakni arus materi, dalam konteks hubungan timbal balik antara sistem sosial dan ekosistem. Ketertindasan kaum buruh tidak hanya berlangsung secara sosial, namun secara fisik berkenaan dengan degradasi kualitas kesehatan mereka sebagai akibat dari lingkungan yang buruk.
Sebagai kelas paling bawah dalam susunan masyarakat kapitalis, kelas pekerja menempati pemukiman yang dibangun tanpa memperhatikan kelayakan infrastruktur dasar. Sekadar udara dan air saja termasuk barang mewah yang hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar. Kaum pekerja mengalami penindasan ganda: secara sosial dan fisik kesehatan akibat lingkungan yang buruk. Engels menyebutnya dengan lantang sebagai Social Murder.
Abdulgani mengetengahkan karya Engels berjudul Dialektika Alam yang dianggap menghimpun khazanah ekologi di dalamnya. Dalam kerangka materialisme historisnya itu, Engels secara rendah hati menyebut alam sebagai entitas “Liyan”; sebab Sang Liyan itu diyakininya akan membalas tindakan manusia setelah berhasil menguasai alam dalam aktivitas kerjanya. Pemikiran Ekologi Engels—secara khusus, dan Marx secara umum—dapat dilihat dari bidang studi antropologi lingkungan atau ekologi manusia.
Merujuk pada catatan Kopnina dan Shoreman-Ouimet ; terdapat empat poin kunci kajian ekologi yang menunjukkan kuatnya relevansi Engels serta pendekatan Ekonomi Politik Marxis: 1. Fokus ekologi manusia beranjak dari komunitas yang dianggap tertutup menuju ke pengakuan bahwa komunitas tersebut merupakan bagian dari ekologi-politik yang lebih luas; 2. Ekologi manusia juga beranjak dari pendekatan sinkronis menuju pendekatan diakronis; 3. Ekologi manusia tidak hanya terlibat dengan politik, tetapi juga menjadi semakin politis; 4. Menguatnya karakter interdisipliner yang dapat melintasi batas-batas antara ilmu alam dan ilmu sosial humaniora.
Engels memberikan penekanan sejak awal bahwa alam, dalam hubungannya dengan aktivitas kerja manusia bukanlah berada pada posisi subordinat, namun secara materialisme dialektika: manusia mengada dalam alam. Ia adalah bagian alam itu sendiri dan karenanya setiap tindakan manusia terhadap lingkungan alam mengandung konsekuensi ekologis dan selanjutnya konsekuensi sosial.
Cara produksi kapitalisme sebagai suatu sistem sosial dalam mengorganisir usaha transformasi alam pada gilirannya telah mendegradasi kelas pekerja sebagai populasi dominan dan mengeksploitasi lingkungan melampaui batas daya dukungnya sehingga memunculkan krisis sosial dan ekologis. Sebagai solusinya Engels mengatakan bahwa ilmu pengetahuan saja tidak cukup. Diperlukan tindakan untuk mengubah keadaan. Tindakan dalam mengubah cara produksi kapitalisme sebagai sebab krisis sosial ekologis lalu diikuti organisasi sosial yang rasional terhadap koevolusi manusia dan alam melalui dukungan ilmu pengetahuan.
Bagian ketiga dari buku ini berbeda dari bagian sebelumnya. Bab yang ditulis oleh Daniel Sihombing ini berisi kritik atas konstruksi Engels terhadap gerakan pemberontakan oleh seorang pendeta Kristen bernama Thomas Müntzer. Engels berusaha mengidentifikasi kesinambungan kegagalan revolusi 1948 di Eropa dengan kejadian tiga abad sebelumnya yang sekaligus menjadi judul karyanya Perang Tani di Jerman. Perang Tani tersebut dianggap sebagai bentuk tradisi panjang perjuangan revolusioner yang ada di masyarakat itu sendiri. Dan revolusi 1848 sendiri hanyalah nafas baru dari tradisi panjang tersebut.
Menurut Sihombing, potret Engels dalam mengkonstruksi Thomas Müntzer ini anakronistik; potret konstruksi Müntzer yang dilakukan Engels:
…Sebagaimana filsafat keagamaan Müntzer itu mendekati atheisme, begitupun program politiknya mendekati komunisme, dan bahkan di ambang Revolusi Februari [1848] banyak sekte komunis masa kini tak punya gudang senjata teoretis selengkap yang Müntzer miliki di abad keenam belas.
Engels melihat itu–teologi Kristen–sebatas sebagai jubah atau selubung dalam pemberontakan melawan tuan tanah yang dipimpin Müntzer. Sedangkan Sihombing mengkritiknya dengan memberikan konteks mengenai konsep Transendensi Radikal–alih-alih atheisme; dan telaah Sihombing atas surat-surat Müntzer yang menguatkan kecenderungan transendensi radikalnya itu.
Konteks transendensi radikal itu adalah pada dua kasus utama: Revolusi Taiping dan Calvinisme. Secara umum, Sihombing tidak setuju sepenuhnya bahwa agama Kristen sebatas “the holy water with which the priest consecrates the heart-burnings of the aristocrat.” Sebaliknya, motif agama justru mampu dijadikan sebagai kekuatan pendorong terjadinya revolusi sosial dari bawah. Motif dorongan itu semakin jelas jika dilihat dalam Magnificat atau Nyanyian Maria ibu Yesus (dalam Lukas 1:52) yang berbunyi,
“Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah”
Motif-motif yang demikian terpampang jelas dalam surat-surat khotbah dan agitasi yang ditulis Müntzer terhadap pengikut juga kepada lawannya. Motif revolusioner Müntzer ini merupakan bentuk transendensi radikal yang luput dari pandangan Engels. Agama sebenarnya mampu mendorong upaya transformasi masyarakat sesuai kondisi Müntzer saat perang berlangsung. Sehingga menurutnya rekonstruksi Perang Tani di Jerman sebagai anakronistik. Namun menurut Sihombing lagi, Engels mengakui peran agama dalam praksis revolusioner di akhir hayatnya namun tak termuat dalam Perang Tani di Jerman. Di luar kritik tersebut terdapat pertanyaan menarik yang diajukan Sihombing, “Bagaimana daya revolusioner yang terpendam dalam keyakinan tentang supremasi Allah dapat diledakkan tanpa terjerumus ke dalam fundamentalisme agama, sosialisme feodal, dan konflik antar agama?”
Ringkasan tiga bagian awal ini adalah bagian dari pemelajaran saya atas Engels—sebagai khazanah keilmuwan sosial ekonomi politik pada umumnya. Pertama kali ditulis untuk kepentingan diskusi dalam forum Rosa Social Studies (RSS) yang diselenggarakan oleh kawan-kawan di Pare. Tokoh underrated ini barang kali masih amat jarang didiskusikan signifikansinya dan oleh karenanya menjadi terlalu sayang jika dilewatkan.
Bagi saya, beberapa hal yang bisa dipetik dari hasil pemelajaran sejauh tiga bab tersebut yang pertama, kebaikan dalam menolong yang lain perlu untuk diantisipasi agar tidak sekadar terjebak pada logika derma kepada yang dikasihani. Perubahan tidak terjadi karena nilai-nilai adilihung bangsawan, kebaikan para penguasa, melainkan diperjuangkan sendiri melalui kesadaran bersama kaum tertindas. Saya melihat bahwa Engels adalah sosok teladan yang lain. Ia ada di batas peperangan batin dan prinsip intelektualnya. Ada di lingkungan serba berkecukupan yang ia sendiri peroleh manfaat darinya, sekaligus mengetahui bahwa kebercukupan itu adalah hasil eksploitasi terhadap kelas pekerja. Engels barangkali berupaya memberi “kompensasi” bagi kelas pekerja yang menghidupinya—dan kelas-kelas borjuis seluruh dunia—dengan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai senjata kelas buruh itu sendiri untuk mengubah nasibnya dan jalan sejarah.
Kedua, briliannya pemikiran seorang Engels yang meski lewat 150 tahun lamanya, tak pernah menjadi usang dan justru menyempurnakan refleksi kritis dalam memberikan solusi atas krisis krusial yang melanda hari ini. Hal itu menandakan, tujuan maupun metode yang digunakannya yaitu Sosialisme Ilmiah dan Materialisme Historis merupakan sumbangan yang masih memiliki tempat yang sangat layak untuk dijadikan pijakan dalam melakukan perjuangan dalam meraih perubahan.
Ketiga dan terakhir, materialisme historis alih-alih merupkan metode atau pandangan alternatif, justru terlampau esensial. Pandangan yang mengutamakan hubungan harmonis, sinergis, dan segala macam perilaku yang diarahkan pada stabilitas, selama ini kita ketahui justru melestarikan berbagai permasalahan mengakar dalam kehidupan sosial politik; membungkam protes; melakukan kekerasan dengan brutal; mencari kambing hitam atas kekacauan timbul; bahkan hingga membredel buku karena dianggap mengajarkan paham radikal, tanpa sedikitpun menyentuh atau sekadar ingin tahu akar penyebab permasalahan yang ada dan bagaimana menuntaskannya.
Engels seperti tak pernah lelah atau sewajarnya membatasi diri dalam tempurung. Ia terus menerobos hingga mencapai titik totalitas dalam melihat masalah, dan memihak kepada mereka yang telah bekerja, bukan yang sekadar pandai menghayati nilai-nilai adiluhung semata. Nampaknya ia adalah orang kaya—dalam moda produksi kapitalisme awal-awal—yang pertama-tama menyadari “dosa” kaumnya, kaum aristokrat borjuis, dan berkomitmen keras untuk mengajak orang-orang sekaligus untuk mengakhiri dosa besar kapitalisme.
Buku terkait yang diulas
-
Friedrich Engels
Original price was: Rp50.000.Rp48.500Current price is: Rp48.500.3% off!
Catatan
- Turba, akronim ‘turun ke bawah’; konsep metode yang digunakan bagi Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) untuk mengilhami gerakan ‘seni untuk rakyat’ lihat Sjafirah 2020 dalam https://indoprogress.com/2020/04/turba-inovasi-khas-indonesia/. Turba memiliki latar belakang yang bisa ditelusuri melalui Dokumen Kongres Nasional I Lekra dengan pidato Njoto yang menerangkan bahwa perjuangan kebudayaan juga harus mampu langsung menyentuh langsung massa rakyat pekerja, lihat Zulfikar 2022:66.