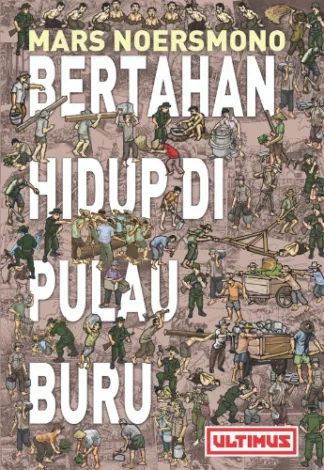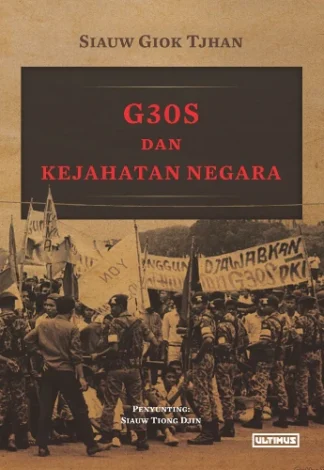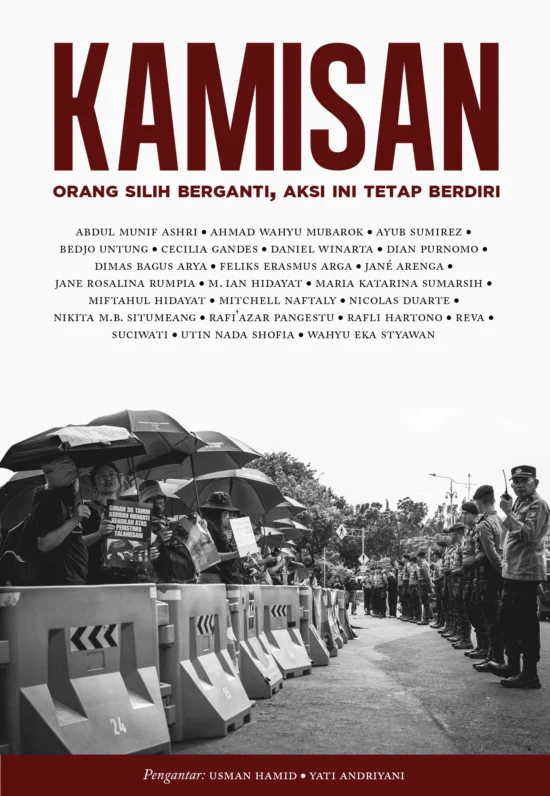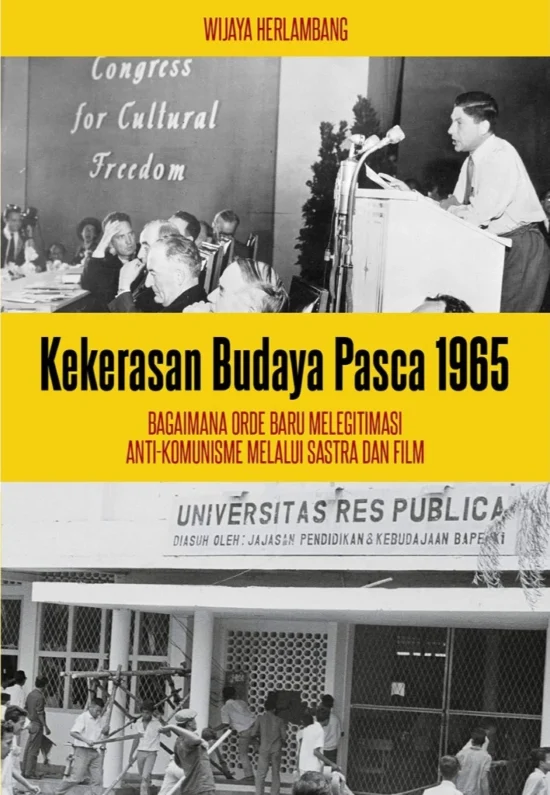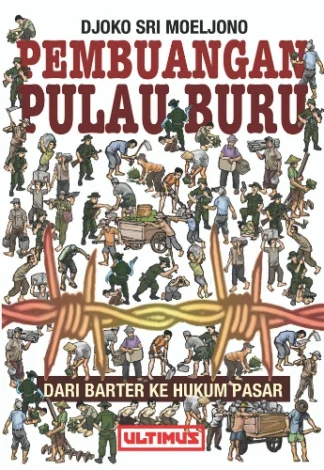oleh

Saat Indonesia memperingati 20 tahun jatuhnya rezim militer Orde Baru, mitos pendirian rezim tersebut (dan tentu saja, negara pasca-Orde Baru) tetap bertahan dan mengakar.
Menurut narasi resmi negara, militer terpaksa turun tangan untuk menyelamatkan negara dari kudeta komunis yang gagal pada dini hari 1 Oktober 1965. Militer dan sumber dari Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa militer bertindak untuk mengakhiri “pemberontakan spontan” oleh “rakyat” — sebuah “ledakan” dari “konflik komunal yang mengakibatkan pertumpahan darah” di seluruh negeri — saat rakyat Indonesia biasa bangkit dalam kemarahan melawan tetangga komunis mereka.
Peristiwa ini, yang secara rahasia dijelaskan oleh CIA sebagai “salah satu pembantaian massal terburuk abad ke-20”, dikenal secara kolektif di Indonesia sebagai “G30S/PKI” — sebuah nama yang menyiratkan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) bertanggung jawab atas kudeta yang gagal yang dipimpin oleh Gerakan 30 September (G30S).
Faktanya, militerlah yang melaksanakan kudeta pada 1 Oktober 1965. Rencana ini dimulai di bawah Demokrasi Terpimpin Soekarno saat militer terlibat dalam perebutan negara Indonesia dengan PKI.
Sekarang ini, kita dapat menjelaskan bagaimana Soeharto menggunakan rantai komando yang ada untuk membawa militer ke kekuasaan. Buku saya, The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder, menunjukkan bagaimana militer menginisiasi dan melaksanakan pembunuhan massal pada tahun 1965-66. Artikel ini berfokus pada mekanisme kudeta militer.
Dr. Jess Melvin adalah Asisten Peneliti Pascadoktoral di Sydney Southeast Asia Centre dan sebelumnya menjabat sebagai Henry Hart Rice Faculty Fellow dalam Studi Asia Tenggara serta Asisten Peneliti Pascadoktoral dalam Studi Genosida di Universitas Yale. Ia menyelesaikan disertasi doktoralnya, “Mechanics of Mass Murder: How the Indonesian Military Initiated and Implemented the Indonesian Genocide: The Case of Aceh,” di Universitas Melbourne pada tahun 2014. Ia juga menulis “The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder,” yang diterbitkan Routledge pada tahun 2018.
Memimpikan kudeta
Pada tahun 1965, militer Indonesia memimpikan sebuah kudeta. Dalam ambisi ini, militer menemukan sekutu kunci dalam pemerintahan Amerika Serikat. Setelah upaya yang didukung AS untuk memisahkan Sumatra dari Indonesia pada akhir 1950-an gagal, militer dan Amerika Serikat menemukan kesamaan pandangan dalam anti-komunisme.
Kepemimpinan militer yang baru bersatu kembali menerima pelatihan dan pendanaan dari AS, yang berharap militer dapat menjadi “negara dalam negara” yang mampu menggulingkan Presiden Soekarno, yang tidak menyembunyikan simpati Marxisnya.
Awalnya, kepemimpinan militer berencana menunggu Soekarno “mundur dari panggung” sebelum bertindak. Namun, rencana militer dipercepat pada Agustus 1965 karena kekhawatiran bahwa Soekarno dan PKI menggunakan kampanye “Ganyang Malaysia” untuk melemahkan monopoli militer atas kekuatan bersenjata.
Sebelum menganalisis bagaimana militer mengambil alih kekuasaan, penting untuk memahami struktur yang dimilikinya pada malam 1 Oktober 1965.
Soekarno, sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, memiliki kendali formal atas angkatan bersenjata. Di bawahnya secara langsung, Panglima Angkatan Bersenjata (Pangad) Jenderal Ahmad Yani memiliki kendali praktis.
Sejak masa revolusi nasional (1945-49), militer diorganisasikan berdasarkan struktur perang teritorial. Komando internal, yang dikenal sebagai Kodam, masih sejajar dengan pemerintahan sipil hingga tingkat desa. Pada 1965, Yani mengendalikan struktur komando Kodam ini.
Yani juga mengendalikan sejumlah struktur komando khusus, termasuk Komando Strategis Kostrad yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, dan Pasukan Khusus RPKAD yang dikendalikan oleh Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.
Selain itu, Yani juga menjabat sebagai kepala staf Komando Operasi Tertinggi (KOTI). KOTI mengoordinasikan keterlibatan militer dalam kampanye Ganyang Malaysia.
Pada Oktober 1964, Komando Mandala Siaga (Kolaga) dibentuk di bawah rantai komando KOTI di Sumatra dan Kalimantan untuk memfasilitasi kampanye Ganyang Malaysia di tingkat lokal. Komandan Kolaga adalah Marsekal Madya Omar Dhani, dengan Soeharto sebagai wakil pertamanya. Dhani kemudian terlibat dalam Gerakan 30 September, dan komando KOTI dan Kolaga menjadi lokasi konflik internal yang signifikan dalam perebutan untuk negara Indonesia.
Brinksmanship1
Pada September 1964, undang-undang disahkan yang memberikan wewenang kepada KOTI untuk secara internal menyatakan keadaan darurat militer tanpa harus terlebih dahulu meminta izin dari Soekarno. Ada kemungkinan Soekarno bermaksud menggunakan perintah KOTI dan Kolaga untuk membantu membawa komunis Indonesia berkuasa. Selain menempatkan sekutunya, Dhani, sebagai komandan Kolaga, Soekarno menyetujui mobilisasi 21 juta sukarelawan pada Mei 1964. Hal ini secara resmi dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi konflik potensial dengan Malaysia, namun militer khawatir sukarelawan tersebut dapat digunakan untuk menentang kekuasaannya sendiri.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika militer juga memanfaatkan undang-undang baru tersebut. Komandan Mandala I di Sumatra, Letnan Jenderal Ahmad Mokoginta yang sangat anti-komunis, menggunakan komando Kolaga untuk memulai uji coba simulasi (dikenal sebagai Operasi Singgalang) mulai Maret 1965, yang menurut laporan bertujuan untuk menilai kesiapan komando militer dalam memobilisasi penduduk sipil. Kelompok-kelompok milisi sipil yang dilatih selama periode ini nantinya akan bertindak sebagai pasukan kejut dalam serangan militer terhadap PKI.
Permainan adu strategi yang berbahaya ini mencapai puncaknya pada Agustus 1965, ketika Soekarno mengumumkan pembentukan “angkatan kelima”, atau tentara rakyat. Meskipun Soekarno mengklaim bahwa kekuatan ini hanya akan digunakan untuk mendukung rencananya dalam menggerakkan warga sipil untuk mendukung kampanye Ganyang Malaysia, militer sangat khawatir. Jika militer tidak lagi memiliki kendali eksklusif atas kekuatan bersenjata di Indonesia, tampaknya tak terhindarkan bahwa PKI akan mencoba merebut kekuasaan.
Militer tidak lagi ingin menunggu Soekarno turun panggung. Sebaliknya, mereka berusaha memicu konfrontasi sesegera mungkin, selagi mereka masih menjadi kekuatan bersenjata terkuat di negara tersebut.
Kekhawatiran utama para pimpinan militer adalah agar mereka tidak terlihat sebagai pihak yang memicu kudeta. Soekarno dan PKI terlalu populer. Sebaliknya, seperti yang dijelaskan John Roosa, militer berharap untuk memicu sebuah “dalih” yang dapat digunakan oleh militer untuk menggambarkan tindakan mereka sebagai tindakan defensif. Tindakan Gerakan 30 September–yang menculik dan membunuh enam anggota pimpinan militer, termasuk Yani, pada dini hari 1 Oktober–memberikan alasan tersebut.
Pendapat saya adalah bahwa tindakan militer selanjutnya memiliki unsur perencanaan awal dan improvisasi: ketika Soeharto merebut kendali negara Indonesia pada pagi hari 1 Oktober, ia mengacu pada perencanaan jangka panjang kepemimpinan militer di bawah Yani, sambil menambahkan sentuhan pribadinya.
Kudeta militer Indonesia pada 1 Oktober 1965
Ketika Gerakan 30 September memenggal kepemimpinan militer pada 1 Oktober, hal itu tidak melumpuhkan komando militer nasional. Sebaliknya, Soeharto mengambil alih kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Yani, dengan sengaja mengabaikan otoritas Soekarno. Soeharto juga mempertahankan posisinya yang strategis sebagai komandan Kostrad, sementara Komandan RPKAD Wibowo akan membuktikan dirinya menjadi salah satu wakil paling setia Soeharto.
Tidak banyak yang tahu bahwa Soeharto juga merebut posisi komandan KOTI. Menariknya, tidak ada indikasi bahwa sekutu Soekarno, Dhani, mencoba menggerakkan KOTI, meskipun secara formal KOTI berada di bawah komandonya pada pagi kritis 1 Oktober.
Sebelumnya diyakini bahwa Soeharto hanya membuat satu pengumuman publik pada 1 Oktober, ketika ia menyatakan bahwa kepemimpinan militer telah “berhasil mengendalikan situasi” dan bahwa baik “pusat” maupun “daerah” kini berada di bawah kendali kepemimpinan militer. Tidak diketahui apa yang dimaksud dengan perintah tersebut. Tidak dapat dibuktikan bahwa Soeharto melakukan kudeta pada 1 Oktober, karena bukti yang ada hanya menunjukkan bahwa ia bertindak secara tidak patuh terhadap Soekarno ketika ia menolak untuk mundur dari jabatan komandan tentara ketika diperintahkan untuk melakukannya.
Kini terungkap bahwa Soeharto jauh lebih aktif dalam mengkonsolidasikan posisinya dan bertindak secara independen dari Soekarno. Bukti dokumen baru menunjukkan bahwa Soeharto mengirim telegram kepada para komandan militer daerah pada pagi hari 1 Oktober dalam posisinya sebagai komandan Angkatan Bersenjata, menyatakan bahwa kudeta yang dipimpin oleh Gerakan 30 September telah terjadi di ibu kota. Perintah ini kemudian diikuti oleh instruksi yang dikirim oleh Komandan Mandala I Sumatra, Mokoginta, yang menyatakan bahwa komandan militer harus “menunggu perintah lebih lanjut”.
Perintah “lebih lanjut” ini datang pada tengah malam hari itu, ketika Mokoginta mengumumkan melalui radio bahwa semua perintah yang dikeluarkan oleh Soeharto harus “dipatuhi”, bertentangan langsung dengan pernyataan Soekarno, yang telah memerintahkan Soeharto untuk mundur. Mokoginta kemudian memerintahkan bahwa “seluruh anggota Angkatan Bersenjata [harus] secara tegas dan tuntas menumpas… sampai keakar-akarnya” semua yang diduga terlibat dalam Gerakan 30 September. Ini adalah contoh pertama yang diketahui dari instruksi semacam itu.
Fakta bahwa Mokoginta mengeluarkan instruksi ini dalam kapasitasnya sebagai Komandan Mandala I sangat signifikan. Kini diketahui bahwa komando Daerah Sumatra diaktifkan pada pagi hari 1 Oktober dengan tujuan eksplisit untuk memfasilitasi kampanye pemusnahan militer. Darurat militer juga diberlakukan di seluruh Sumatra.
Sementara itu, di Jakarta, Kostrad dan RPKAD digunakan untuk secara fisik menumpas Gerakan 30 September pada tanggal 1 hingga 2 Oktober, dan pada tanggal 3 Oktober, keadaan perang dideklarasikan di sana. Selama beberapa hari berikutnya, Soeharto menuntut janji setia dari para komandan militer di seluruh negeri sementara media dibungkam dan pemimpin sipil dilumpuhkan.
Pengambilalihan kendali atas sayap militer negara Indonesia dan subordinasi ruang sipil di bawah kendali militer mencapai puncaknya dalam pidato Hari Angkatan Bersenjata Soeharto pada 5 Oktober di Jakarta. Sementara Soekarno ragu-ragu, Soeharto secara terbuka menetapkan dirinya sebagai pembuat keputusan yang tak terbantahkan pada saat itu. Soeharto tidak mendeklarasikan kudeta pada 1 Oktober karena dia tidak perlu melakukannya.
Rantai komando yang berlapis-lapis
Pembantaian dimulai beberapa hari setelah militer mengambil alih kendali negara Indonesia. Terdapat fase-fase kekerasan yang terlihat jelas. Setelah pertama kali menyatakan niatnya untuk “memusnahkan” Gerakan 30 September pada tengah malam 1 Oktober, militer memerintahkan warga sipil untuk ikut serta dalam kampanye militer mulai 4 Oktober. Kemudian, militer mendirikan “Ruang Perang” di Aceh pada 14 Oktober dengan tujuan eksplisit untuk memfasilitasi kampanye pemusnahan tersebut. Setiap prosesnya, tindakan militer dikoordinasikan melalui sistem komunikasi dua arah yang rumit, yang menjangkau hingga tingkat desa. Militer menggunakan rantai komando ganda untuk melaksanakan kampanye ini secara nasional.
Aksi Gerakan 30 September membagi Indonesia menjadi empat wilayah komponen: Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Militer memfokuskan fase pertama serangannya di Sumatra dan Jawa, dua pusat ekonomi dan populasi utama negara, sebelum memperluas jangkauannya ke luar. Saat militer mulai bergerak untuk melaksanakan “operasi penumpasan” terhadap kelompok yang mereka sebut kelompok komunis Indonesia, pembagian tugas mulai berkembang di seluruh negeri.
Di Sumatra, langkah paling masuk akal bagi pimpinan militer adalah memanfaatkan KOTI, Kolaga, dan komando regional di bawah kepemimpinan Mokoginta secara keseluruhan di Sumatra. Dokumen internal Kedutaan Besar AS menunjukkan bahwa Sumatra digunakan sebagai “kasus uji coba” oleh militer pada saat itu karena kemampuan militer untuk menerapkan darurat militer secara internal. Hal ini berarti kepemimpinan militer dapat mengendalikan tidak hanya pasukan bersenjata tetapi juga penduduk sipil di wilayah tersebut. Pembunuhan massal dimulai di wilayah tersebut pada 7 Oktober, dan berkembang menjadi pembunuhan massal sistematis mulai 14 Oktober.
Di Jawa dan Bali, militer mengoordinasikan serangannya melalui komando Kostrad dan RPKAD. Komando-komando ini, secara alamiah, sangat mobile. Mereka juga dapat beroperasi secara independen dari komando Kodam setempat yang, setidaknya di Jawa, dianggap telah terpengaruh atau bersimpati terhadap Gerakan 30 September. Satu-satunya tempat di mana komando-komando militer setempat secara nasional mendukung Gerakan 30 September adalah di Jawa Tengah (meskipun baik Bali maupun Sumatra Utara memiliki gubernur yang berafiliasi dengan PKI).
Kostrad pertama kali digunakan untuk menumpas Gerakan di ibu kota sebelum dikirim untuk memimpin serangan militer di Jawa Tengah mulai 18 Oktober. Pada Desember, RPKAD pindah ke Bali. Komandan RPKAD juga ditugaskan untuk mengoordinasikan jaringan nasional regu pembunuh sipil.
Di Kalimantan, militer memiliki komando Mandala sendiri di bawah komando KOTI dan Kolaga, sama seperti di Sumatra. Namun, meskipun komando Mandala II di bawah Mayor Jenderal Maraden Panggabean memiliki potensi operasional yang sama dengan Mandala I, tampaknya kampanye pemusnahan oleh militer tidak dimulai di wilayah tersebut hingga Oktober 1967. Demikian pula, kampanye pemusnahan oleh militer di Indonesia Timur tidak dimulai hingga Desember 1965.
Alasan penundaan ini tampaknya terkait dengan berkurangnya kepentingan strategis wilayah-wilayah tersebut bagi pemerintah pusat. Baik Sumatra maupun Jawa merupakan pusat populasi dan ekonomi yang penting, sementara Bali, yang dikenal sebagai pusat PKI, menjadi prioritas serangan gelombang kedua militer. Seiring dengan perluasan kendali militer, skala pembunuhan pun semakin meluas.
Upaya untuk mengonsolidasikan kampanye pembasmian militer dilakukan pada akhir 1965. Soeharto membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 6 Desember. Meskipun komando ini mendapat banyak perhatian karena perannya dalam mengoordinasikan serangan militer, sebenarnya komando ini tidak relevan pada tahap awal kampanye pembasmian militer. Pembantaian terburuk di Aceh, misalnya, di mana kampanye tersebut pertama kali dimulai, telah berakhir pada saat Kopkamtib didirikan di Sumatra.
Bahwa kepemimpinan militer nasional memilih untuk mengoordinasikan kudeta dan kampanye pembantaian selanjutnya melalui jaringan rantai komando semi-otonom dan spesifik wilayah tidak mengurangi sifat sentralisasi dari koordinasi militer di balik genosida tersebut. Pendekatan semacam tidaklah unik untuk Indonesia. Holocaust Nazi juga dikoordinasikan melalui berbagai rantai komando dan spesifik wilayah.
Tingkat koordinasi inilah yang memungkinkan pola-pola nasional yang begitu jelas berkembang dalam pembunuhan-pembunuhan selanjutnya. Tujuan akhir kekerasan ini adalah untuk mengkonsolidasikan pengambilalihan kekuasaan negara oleh militer.
Sekarang jelas bahwa Soeharto memainkan peran koordinasi sentral di balik kudeta militer dan kampanye pemusnahan selanjutnya. Militer tidak dengan enggan turun tangan untuk menyelamatkan negara dari kudeta pada 1 Oktober 1965. Sebaliknya, militer secara aktif bekerja untuk merebut kekuasaan bagi dirinya sendiri, menggunakan aksi Gerakan 30 September sebagai katalisator pelaksanaan rencana jangka panjang untuk melaksanakan kudeta mereka sendiri.
Dalam memimpin pada hari penting ini, Soeharto tidak hanya merespons aksi Gerakan 30 September, tetapi juga mengandalkan perencanaan jangka panjang kepemimpinan militer nasional. Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi kemudian digunakan untuk menakut-nakuti penduduk dan mencegah segala bentuk perlawanan terhadap rezim militer baru.
Trauma dari periode ini masih menghantui Indonesia hingga saat ini. Dua puluh tahun setelah Reformasi dan 53 tahun sejak Orde Baru berkuasa, sudah saatnya untuk mulai berbicara secara terbuka tentang kudeta militer Indonesia pada tahun 1965. Untuk benar-benar memutus propaganda Orde Baru, perlu untuk membalikkan versi militer tentang peristiwa-peristiwa ini. Peristiwa-peristiwa ini, menurut saya, sebaiknya dikenal sebagai “G30S/Militer”.
Baca juga buku-buku tentang Orba berikut:
-
Kamisan
Rp71.000
Catatan
- Brinksmanship merupakan tindakan mendorong suatu keadaan berbahaya ke ambang kehancuran untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Brinkmanship diterapkan dalam politik internasional, kebijakan luar negeri, hubungan tenaga kerja, dan strategi militer yang melibatkan ancaman senjata nuklir, dan tuntutan hukum tingkat tinggi. Dalam konteks sejarah Indonesia, dapat melihat bagaimana militer mendorong kekacauan ke arah kehancuran untuk melaksanakan rencana jangka panjangnya dan meraih kekuasaan